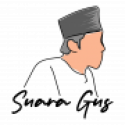Demokrasi Amerika ternoda oleh ulah pendukung Trump. Mereka memaksa masuk ke gedung Capitol Hill tempat anggota kongres akan memutuskan hasil Pilpres Amerika November kemarin. Merangseknya pendukung Trump hingga ke altar mimbar sungguh di luar dugaan dan membuat kaget warga dunia. Capitol Hill yang laksana rumah suci demokrasi yang dijaga kesakralannya dan tidak memasukinya kecuali orang formal dan serbaformal, tiba-tiba diserbu kerumunan yang mengabaikan code of conduct. Mereka menolak pengesahan Joe Biden sebagai pemenang pilpres. Sistem keamanan negeri Paman Sam yang terkenal top ternyata tidak mampu mencegah itu. Sungguh di luar dugaan.
Demokrasi Amerika yang anggun dan berwibawa seolah tumbang di era Donald Trump. Perjalanan demokrasi yang dibangun selama 2,5 abad hingga tercipta sistem check and balance, norma dan etika demokrasi yang baik kini berada dalam performa rendah. Alex Tan dari Universitas Cantenbury New Zealand mengatakan bahwa kondisi demokrasi Amerika harus diwaspadai. Penurunan kualitas ini bisa berakibat pada munculnya fasisme seperti di Jerman pada 1930. Pada saat itu muncul Nazi yang menggelorakan kemuliaan Jerman di antara bangsa-bangsa lain.
Jargon Trump dalam kampanye “Make America Great Again” (MAGA) mengarah ke sana. Mengembalikan Amerika hebat kembali artinya menjadikan Amerika unggul di antara bangsa-bangsa lain, sebuah kebanggaan fasis. Gaya Trump dalam berpidato yang tak ubahnya orator zaman perang yang kerap menjunjung diri sendiri dan menyerang lawan adalah gaya fasis yang sudah lama ditinggalkan pemimpin Amerika. Dari Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Hussein Obama Jr., mereka menjaga kata-kata dalam pidatonya dan jauh dari sarkasme. Trump membalik tradisi itu. Gelaran pilpres yang lebih lima dekade mulus selalu diterima dengan lapang dada oleh yang kalah sembari memberikan pidato pengakuan kekalahan seperti yang dilakukan Hillary Clinton saat kalah oleh Trump, ditarik mundur. Donald Trump menggugat di pengadilan dan tatkala ditolak, terus melawan hingga kejadian massa merangsek ke altar Capitol Hill.
Kemampuan mengendalikan diri politisi menjadi ciri khas kemapanan demokrasi negara maju. Mereka yang telah berperang di Perang Dunia I dan II dengan korban nyawa jutaan telah sadar akan mahalnya perdamaian dalam segala hal khususnya politik. Permusuhan antarblok mereda dan mereka memasuki Wisdom Era, kata Dalia Mogahed warga Amerika keturunan Mesir penasihat presiden Obama untuk urusan Timur-Tengah. Sebuah era yang mengedepankan kepentingan orang banyak dan bukan semata kepentingan sendiri. Inilah mengapa negara maju mau menerima pengungsi korban konflik Suriah meski mereka dari “lawan” peradaban (meminjam istilah Samuel P. Huntington, Clash of Civilizations). Itu karena wisdom yang oleh Trump dibatalkan dengan alasan kepentingan nasional.
Selain wisdom yang bukan lagi menjadi core–value Trump dalam hubungan global, presiden dari partai Republik ini menjadikan gaya demagog muncul kembali dalam blantika politik Amerika yang sebenarnya sudah out of date. Demagog adalah pemimpin politik yang mengandalkan retorika membela kepentingan rakyat untuk melawan pemerintah. Demagog menjadikan pemerintah sebagai kelompok elite yang tidak berpihak kepada rakyat. Dia tampil di depan untuk memperjuangkan itu. Dengan kemampuannya mempengaruhi massa lewat pidatonya yang provokatif, dia mampu merenggut hati massa dan meraup dukungan. Demagog kadang berhasil kadang gagal. Kalau berhasil, dia akan cenderung otoriter dan dengan mudah menyingkirkan lawan karena dianggap tidak berpihak pada rakyat. Padahal, mengubah nasib rakyat tidak sesederhana membalik tangan dan butuh waktu lebih 20 tahun. Demagog kalau jadi dipastikan akan memperpanjang masa berkuasa karena 5 tahun terlalu pendek untuk itu. Pembelahan masyarakat antara pendukung elite penguasa dan pembela rakyat berdampak buruk bagi kesatuan bangsa. Dalam demokrasi yang bertumpu pada rotasi kepemimpinan periodik melalui pemilu, penyebutan elite penguasa tidaklah relevan kecuali untuk internal politisi. Dengan kekuasaan yang dibatasi maksimal 2 periode, istilah elite penguasa kurang relevan karena ke depan pasti diganti. Belum lagi keberadaan oposisi yang tidak pernah mengakui kesuksesan penguasa, maka sebutan elite penguasa cenderung politis.
Sebagai soko guru demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada politik jangka pendek tapi kemaslahatan jangka panjang dan luas bahkan lintas peradaban, munculnya karakter demagog pada presiden Amerika menjadi aneh. Pemimpin negara saat ini lebih tampak cool daripada berapi-api. Lebih tampak careful daripada careless. Dan itu bertolak belakang dengan karakter Trump yang retorik dan provokatif. Gaya Trump cocok untuk masa 60-an saat John F. Kennedy dan Soekarno berkuasa, bukan saat ini. Trump salah waktu alias anakronistik, tapi apa boleh buat, saat itu dia masih remaja belum waktunya jadi presiden.
Achmad Murtafi Haris, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya